Dekonstruksi
Derrida
Jacques Derrida
merupakan filsuf keturunan Yahudi yang lahir pada 15 Juli 1930 di Aljazair.
Pemikiran Filsuf ini termasuk dalam postmoedernis. Teorinya adalah dekonstruksi,
yang menyita banyak perhatian filsuf lainnya. Akan tetapi sebelum membahas
terlalu jauh tentang Derrida dan pemikirannya, alangkah lebih baik kita
membahas Hermeneutika terlebih dahulu.
Hermeneutika oleh Gadamer merupakan suatu upaya untuk
menafsirkan teks. Tafsiran ini
dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tertentu. Terdapat dua konsep inti di dalam hermeneutika
Gadamer. Konsep inti tersebut
adalah peleburan
horison-horison (fusion of horizons).
Konsep ini berisi penjelasan
Gadamer mengenai proses penafsiran yang melibatkan isi asli teks sekaligus
pikiran maupun perasaan orang yang membacanya. Selanjutnya, konsep
kedua adalah lingkaran hermeneutik. Pada konsep ini berisikan penjelasan
Gadamer tentang bagaimana proses
untuk memahami suatu teks. Teks baru bisa dipahami manakala terdapat pemahaman dari
tiap bagiannya. Untuk memahami bagian-bagiannya, perlu dipahami terlebih dahulu
maknanya. Sehingga, setiap bagian dalam suatu teks memiliki koherensi. Saat
keduanya dileburkan, akan menghasilkan tafsiran yang
menciptakan pemahaman yang baru.
Pemikiran dari Derrida memang terlalu sulit untuk difahami. Akan tetapi,
terdapat dua kata kunci untuk
memahami hermeneutik Derrida,
antara lain adalah dekonstruksi dan Differance.
Menurut Derrida sendiri
dekonstruksi bukanlah sebuah motode atau teknik atau sebuah gaya kritik
sastra atau sebuah prosedur untuk menafsirkan teks. Dengan kata lain
adalah sebuah metode sekaligus melampaui metode itu sendiri. Derrida mengadaptasi kata dekonstruksi dari destruksi Heidegger.
Mengubah realitas menurut Derrida berarti mengubah
teks. Teks
itu sendiri adalah realitas kehidupan manusia. Untuk mengubah realitas seseorang sebelumnya harus mampu memahami
dan menggambarkan realitas. Ada keterkaitan yang mendalam antara menggambarkan
(to describe) dan mengubah (to transform).
Dekonstruksi (metode
dalam pembacaan teks)
merupakan suatu metode pembacaan teks, yang menolak adanya absolutisitas
tentang suatu kebenaran yang dikandung.
Interpretasi atas suatu teks dipengaruhi oleh sejarah yang membentuknya, dan tidak ada makna final atau universal atas suatu teks.
Menurut dekonstruksi Derrida hal-hal yang sudah benar dalam pembacaan teks,
belum tentu benar demikian.
Bila dilihat dari sisi
sejarahnya ada beberapa hal yang
tersembunyi.
Suatu yang sudah dibenarkan menurut pendapat perseorangan
Derrida dicoba untuk dipahami dengan sebuah dekonstruksi dimana dibalik
kebenaran yang telah diyakini oleh semua orang tersebut terdapat suatu
kontradiksi yang tersembunyi.
Konsep Derrida tentang dekonstruksi,
secara implisit meramalkan suatu kekuatan superfisialitas dalam filsafat.
Ramalan ini tersingkap dalam pendiriannya yang secara radikal menolak “logosentrisme ”,
yaitu pemikiran tentang “ada sebagai kehadiran”. Logosentris di sini dapat diartikan dengan penafsiran teks yang didominasi
kelompok atau perseorangan.
Bagi
Derrida, dekonstruksi digunakan
sebagai strategi filsafat, politik,
dan intelektual dalam
upaya membongkar modus membaca
dan menginterpretasi yang mendominasi dan menguatkan fundamen hierarki. Dalam artian, dekonstruksi merupakan salah satu strategi untuk
menguliti lapisan-lapisan makna yang terdapat di dalam "teks", yang
selama ini telah ditekan atau ditindas. Bagi Derrida, tidak ada yang eksis di
luar "teks", realitas sesungguhnya tidak ada karena semua realitas dikonstruksi secara budaya, linguistik atau
historis, hanyalah "teks" saja. Oleh sebab itu, realitas
terdiri dari berbagai "teks" dengan kebenaran yang plural. Maksudnya, tidak ada kebenaran universal. Sifat permanen
tidak melekat pada teks. Sehingga, teks selalu bisa dibaca dan dimengerti
dengan cara yang selalu berbeda. Dominan tidak berlaku di sini.
Differance berasal dari kata Perancis. Saat diucapkan
pelafalannya persis sama dengan kata difference.
Kata-kata ini berasal dari kata differer
yang bisa berarti “berbeda” sekaligus “menangguhkan/menunda.” Dalam membedakan makna
differance dan difference, kita tak hanya dengan mendengar ujaran karena
pelafalannya sama, tetapi harus melihat tulisannya. Ini membuktikan tulisan
lebih unggul daripada ujaran, seperti apa yang dipikirkan Derrida.
Di sini Derrida menunjukkan
kelemahan dari ucapan untuk mengungungkapkan makna dengan menggunakan kata différance. Differance
berasal dari kata difference yang mencakup tiga pengertian, yaitu:
1. to differ untuk membedakan
2. differe (Latin) untuk menyebarkan,
3. to defer untuk
menunda.
Konsep différance ini sendiri dilatarbelakangi dengan adanya keinginan Derrida untuk mencoba menemukan bagaimana bahasa mempunyai arti. Saat itu, ia tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh kaum
modernis yang sering keliru karena meletakkan ”arti” dalam kekuatan rasio. Terlebih lagi, kalimat manusia sering digunkaan untuk menggambarkan realitas yang sebenarnya dalam kehidupan manusia. Di sini, jalan bagi Derrida untuk mengkritik tradisi barat. Mereka (tradisi barat) menyatakan bahwa tulisan hanyalah gambaran atau representasi
dari ucapan manusia. Hal ini dikarenakan ucapan lebih langsung sifatnya dibandingkan dengan
tulisan.
Memahami Dekonstruksi Derrida dalam Kacamata Islam
Dekonstruksi Derrida sendiri bila diulik dari kacamata agama, mempunyai dimensi teologis. Dekonstruksi lebih menunjuk pada ketidakmungkinan untuk membicarakan Tuhan
karena pengaruh dan efek dari difference
muncul dari penghormatan yang lain. Selanjutnya, dekonstruksi
memperlihatkan dalam mencapai kebenaran atau kebenaran yang-tak-mungkin,
berasal dari tidak adanya lagi horizon pemaknaan yang dapat dibangun
untuk mengetahui kebenaran.
Derrida juga berbicara tentang iman akan
yang tak-mungkin. Derrida
merasakan hasrat yang lain dalam arti
hasrat dan gairah religius yang melampaui dogma. Ini dapat dibuktikan dengan pengalaman religius Derrida yang menganut agama Yahudi
sejak kecil, tetapi akhirny beralih dari agama Yahudi dan masuk ke 'agama tanpa-agama'
yaitu agama yang lebih merupakan pengalaman religius dan cara pandang dalam
mendekati Ilahi sebagai yang-tak-mungkin.
Mari kita ambil satu kasus dalam pemahaman
dekonstruksi Derrida ini. Bom Bali tahun 2002 di Legian dan berbeagai aliran
dalam agama Islam contohnya. Pemboman ini dilakukan oleh teroris, yang
notabenenya berasal dari kaum muslimin. Agama Islam adalah satu kepercayaan dengan
satu kitab, akan tetapi bercabang menjadi banyak sekali aliran (70 sekian).
Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Islam
yang notabenenya memiliki hanya satu kitab suci, tetapi memiliki hampir 70
sekian aliran, seperti NU, Muhammadiah, HTI, LDII, dan yang sangat mengundang
perhatian publik adalah, munculnya aliran baru yang diyakini sebagai aliran
sesat, Ahmadiah. Hal demikian terjadi karena, penafsiran dari ayat suci atau
yang kalau disebut Derrida di sini teks adalah berbeda-beda setiap orang dan
golongan. Perbedaan tersebut dikuatkan oleh masing-masing golongan yang
percaya, dilestarikan, hingga dalam satu agama Islam memiliki banyak aliran.
Sayangnya,
penafsiran teks ini juga melahirkan aliran sesat, bahkan sampai ada juga yang
mengaku sebagai nabi terakhir. Yang menjadi pertanyaan bila dipandang dari
teori dekonstruksi, apakah “tersangka” yang dipenjarakan karena mengaku sebagai
nabi terakhir ini benar-benar nabi? Di Al-Quran sendiri tertulis nabi terakhir
adalah nabi Muhammad SAW. Itulah yang nampak pada realitas kita sebagai orang
kebanyakan. Jangan-jangan hanya kita saja yang salah mengartikan, bahwa nabi
terakhir yang ditulis di teks kitab suci adalah Nabi Muhammad? Atau
jangan-jangan “tersangka” itu saja yang sudah salah mengartikan teks Al-Quran
tersebut? Si “tersangka” dapat berkata demikian, karena dia tidak menelan
mentah-mentah begitu saja apa yang ada dalam teks Al-Quran. Dia mencoba
mengkritisi pemaknaan bahasa di balik realitas tersebut. Yang menjadi
permasalahan adalah, sebuah pertanyaan besar kita, siapa yang benar dan salah
dalam mengartikan teks Al-Quran di sini? Mengingat, pemaknaan berbeda dalam
teks Al-Quran juga tidak terdapat dalam aliran-aliran di agama Islam dan
pengakuan manusia “tersangka” sebagai nabi terakhir ini saja.
Di dalam kitab kuning tersebut juga, Tuhan
memberikan wahyu bahwa penganut agama Islam hendaknya memerangi orang kafir. Dalam
sejarah Islam, banyak sekali perang antara kaum muslimin yang dikomandoi Nabi
dan Rosul untuk memerangi kaum Kafir Quraisy. Alhasil banyak sekali teroris
berkedok kaum muslim melakukan penyerangan tersebut dalam bentuk pemboman suatu
tempat, seperti Bom di Legian Bali, Hotel JW Mariot, dan masih banyak lagi.
Lokasi Legian Bali sendiri dipilih karena, di Legian terdapat banyak kafe,
diskotik, bar, hotel, dan tempat-tempat hiburan malam lainnya yang dianggap
teoris sebagai tempat berkumpulnya kaum kafir. Maka tak tanggung-tanggung
teroris mengebom tempat tersebut, yang mereka namakan sebagai memerangi kaum
kafir.
Dalam hal ini, teroris sudah menyalahi
aturan. Apakah benar demikian? Atau kita saja yang sudah salah memahami
perintah Al-Quran? Menurut Derrida, kita tidak bisa menelan mentah-mentah suatu
teks. Di suatu kebenaran, pasti terdapat kebenaran lainnya. Iya, memang benar
bahwa kaum muslim diperintahkan untuk memerangi kaum kafir. Tapi coba sama-sama
kita tilik pada penafsiran teks lainnya. Perintah itu turun di zaman sejarah, dengan
kondisi yang sudah jauh berbeda dengan sekarang ini. Zaman sejarah adalah zaman
di mana masa perjuangan penyebaran Islam yang diwarnai dengan perang, sehingga
untuk bertahan pun harus dengan strategi perang juga. Tentu hal tersebut
berbeda dengan zaman sekarang bukan? Terlebih lagi, pemboman di Legian bali ini
juga sama-sama merengut nyawa beberapa kaum muslimin yang tidak berdosa. Lalu,
sebenarnya teroris itu adalah sekumpulan manusia penderita psikopat, ataukah
sekumpulan orang yang salah menafsirkan teks Al-Quran? Atau bahkan, mereka
adalah sekumpulan manusia yang sudah benar dalam menafsirkan teks Al-Quran?
Pelajaran yang dapat kita ambil di sini, adalah
tentang pilihan kita secara moral. Seperti yang dikatakan Derrida, kita boleh
dan dibebaskan mengartikan suatu “teks” dengan berangkat dari balik realitas
tersebut. Akan tetapi, setidaknya pemikiran kita harus bisa
dipertanggungjawabkan. Apakah kita akan mengartikan suatu “teks” dengan
mengambil tindakan yang bisa merugikan orang lain, atau tindakan yang bisa bermanfaat
dan membuat orang lain merasa nyaman.
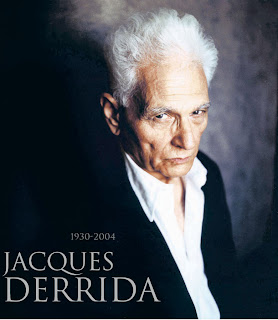

Tidak ada komentar:
Posting Komentar